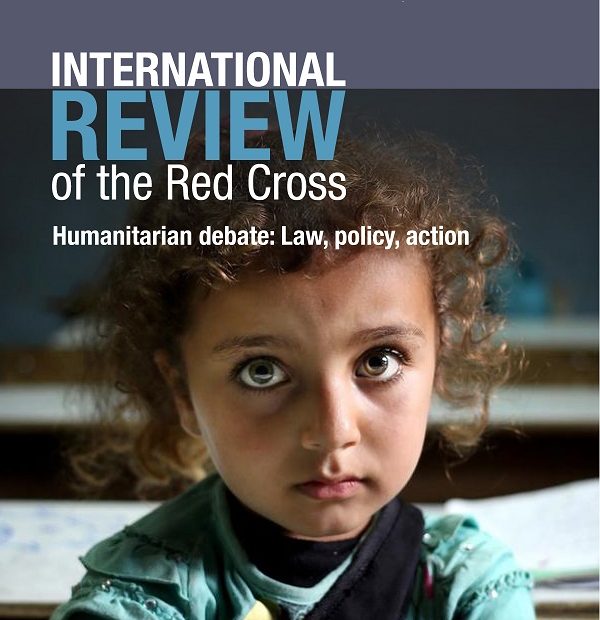Bahkan selama konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya, semua anak berhak atas hak dan pelindungan sebagai anak-anak tanpa membedakan usia, jenis kelamin, agama, atau apakah mereka terkait dengan kelompok bersenjata. Meskipun demikian, jutaan anak di zona konflik menghadapi diskriminasi, pengasingan, dan stigmatisasi. Hal ini terutama berlaku untuk anak-anak yang berafiliasi dengan kelompok yang ditunjuk sebagai “teroris”, yang menghadapi berbagai tantangan dalam berintegrasi kembali ke masyarakat. Masyarakat sipil dapat memainkan peran penting di tingkat internasional, regional dan domestik dalam membantu anak-anak yang sebelumnya terkait dengan kelompok bersenjata, atau dipengaruhi oleh konflik bersenjata, untuk bergabung kembali dengan masyarakat. Mira Kusumarini adalah seorang profesional di bidang perdamaian dan keamanan di Indonesia yang bekerja mengatasi masalah perempuan dan anak-anak yang terkait dengan kelompok bersenjata, dan membantu mengintegrasikan mereka kembali ke masyarakat. Ia adalah Direktur Eksekutif Coalition of Civil Society Against Violent Extremism (C-SAVE), sebuah jaringan kolaboratif antarorganisasi masyarakat sipil. Dalam wawancara ini, ia membahas tantangan dalam reintegrasi anak-anak yang dikaitkan dengan kelompok ekstremis di Indonesia dan stigma yang mereka hadapi, serta pentingnya empati dalam membantu masyarakat untuk sembuh.
Anda telah terlibat dalam pekerjaan beberapa LSM di Indonesia selama bertahun-tahun, mengerjakan berbagai isu hak asasi manusia. Apa yang mendorong Anda dalam pekerjaan ini?
Dorongan utama pekerjaan saya adalah perhatian saya pada empati. Meskipun empati sangat penting dalam kehidupan sosial kita, hal itu tidak menjadi perhatian utama kebanyakan orang saat ini. Satu dasawarsa terakhir saya disibukkan dengan kegiatan perdamaian di Jakarta, dan saya ikut mendirikan C-SAVE sekitar empat tahun yang lalu.
Sebelum bergabung dengan C-SAVE, saya bekerja mengarusutamakan kewirausahaan sosial, di mana empati terapan digunakan sebagai pendorong utama untuk solusi sosial yang inovatif. Saya memulai Empatiku [My Empathy] Foundation untuk mengutamakan kompetensi emosional dan menjadikan empati sebagai prioritas dalam pendidikan dini seperti halnya mata pelajaran akademik lainnya.
Pada 2016, ketika C-SAVE pertama kali didirikan, kami mulai mengadvokasi perubahan hukum dan kebijakan penanggulangan terorisme/ counterterrorism [CT] nasional . Proposal berupa daftar inventaris masalah [DIM], dirumuskan terhadap rancangan revisi UU Penanggulangan Terorisme No. 15/2003. Substansi proposal ini berkisar pada sembilan tema. Selain menempatkannya di DIM, Koalisi juga mengedepankan argumen yang diajukan melalui makalah kebijakan yang berbeda. Dari sebelas perubahan substansial dalam rancangan UU CT, delapan usulan Koalisi untuk lebih melindungi hak asasi manusia ditampung.
Pada saat itu, media melaporkan bahwa beberapa orang Indonesia melakukan perjalanan ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan kelompok ISIS. Aktivis dan LSM Indonesia tahu bahwa beberapa orang bisa kembali ke Indonesia untuk merekrut orang lain. Namun, baru pada 2017 lah dikonfirmasi ada sekelompok orang Indonesia yang terkait dengan IS ditahan dan dikirim kembali ke Indonesia, sebagian besar dari Turki. Pada saat itu ada sekitar 75 orang yang telah kembali, dan pemerintah Indonesia telah merujuk ke pusat-pusat rehabilitasi yang dijalankan oleh Kementerian Sosial.
Ini adalah titik awal kerja C-SAVE dengan orang-orang yang dideportasi dan yang kembali dan dikaitkan dengan kelompok teroris seperti IS. Dari tujuh puluh lima orang yang dikembalikan, hampir 50% adalah anak-anak, sekitar 35% adalah wanita dan sisanya adalah laki-laki. Tujuan kami adalah untuk memastikan bahwa mereka terintegrasi kembali ke masyarakat sehingga mereka bisa terus menjalani kehidupan normal.
Saat mereka yang dideportasi ini dirujuk ke pusat rehabilitasi, C-SAVE melihat bahwa tidak ada program untuk rehabilitasi dan reintegrasi mereka. Pemerintah dan pekerja sosial yang bekerja di sana tidak menyadari bagaimana menangani masalah ini atau bahkan bagaimana memahami masalah ini secara komprehensif. Di sinilah kami masuk, dan kami menawarkan untuk memberikan dukungan kepada pekerja sosial di pusat-pusat. Dari sini lalu kami bekerja sama dengan kementerian dan institusi terkait untuk membantu menciptakan prosedur operasi standar untuk rehabilitasi dan reintegrasi orang-orang yang dideportasi dan mereka yang kembali ke Indonesia. Sejak saat itu, telah ada sekitar 490 orang yang telah melalui program rehabilitasi dan reintegrasi yang dijalankan oleh Kementerian Sosial. Prosedur Operasi Standar untuk Rehabilitasi dan Reintegrasi Individu yang Sudah Terekspos Ideologi Terorisme Radikal [SOP] adalah seperangkat instruksi langkah-per-langkah yang disusun oleh Kementerian Sosial untuk membantu pekerja sosial melakukan operasi rutin yang kompleks dalam memberikan layanan rehabilitasi dan reintegrasi. SOP ini bertujuan untuk mencapai efisiensi, output berkualitas dan keseragaman kinerja, sekaligus mengurangi miskomunikasi dan kegagalan untuk mematuhi aturan dan tata tertib terkait. SOP berisi aspek rehabilitasi yang disampaikan oleh pusat rehabilitasi dan reintegrasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Kami, sebagai organisasi masyarakat sipil, telah ada untuk meningkatkan kapasitas pekerja sosial dan kerangka kebijakan di pusat-pusat.
Mengapa reintegrasi orang, dan khususnya anak-anak, yang pernah dikaitkan dengan kelompok bersenjata sangat penting bagi masyarakat? Apa peran empati dalam proses ini?
Rehabilitasi dan reintegrasi orang-orang ini penting karena mereka juga manusia. Penting bagi mereka untuk pulang ke rumah dan dapat bergabung kembali dengan masyarakat dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi warga negara normal lagi, sama seperti kita semua. Anak-anak adalah korban paling rentan dari ideologi ekstremis kekerasan. Hampir separuh dari mereka yang dideportasi dan yang kembali berusia di bawah 18 tahun, termasuk balita (48%), anak-anak usia 6-12 tahun (42%), dan remaja 13-18 tahun (10%). Berdasarkan data dari lapangan, anak-anak yang dideportasi dan kembali ini mengalami trauma psikologis dan selama ini berada di lingkungan yang berpotensi mengancam kehidupan dan kesehatan fisik dan mental mereka.
Kami belajar bahwa salah satu keterampilan penting yang memungkinkan anak-anak untuk dapat kembali ke masyarakat adalah empati — tidak hanya keterampilan empati anak-anak itu sendiri, tetapi juga penting bagi pekerja sosial untuk memaksimalkan keterampilan empati mereka demi memahami situasi anak-anak agar dapat membantu mereka dengan lebih efisien. Tujuan kami adalah untuk memastikan bahwa orang-orang yang dideportasi dan yang kembali dapat kembali ke komunitas lokal mereka dan menjalani kehidupan normal. Adalah penting untuk memanfaatkan empati sebagai keterampilan, karena hal itu yang menjadi dasar untuk memastikan terintegrasinya orang-orang tersebut kembali ke masyarakat.
Tujuannya bukan untuk de-radikalisasi, tapi lebih sebagai langkah pertama untuk mengisi kekosongan dalam keterampilan sosial mereka dengan memasukkan empati sebagai kompetensi dasar, dan untuk membekali mereka dengan keterampilan sosial lain yang relevan sehingga memungkinkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Karena itu, kami memberikan pelatihan empati bagi pekerja sosial, selain pelatihan komunikasi dan keterampilan lainnya.
Memastikan hak-hak anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata itu rumit. Apa saja tantangan yang dihadapi anak-anak yang terkait dengan kelompok bersenjata ketika mereka kembali ke komunitas mereka?
Seperti yang Anda sebutkan, berurusan dengan anak-anak yang terkena konflik bersenjata adalah masalah multi-dimensi. Salah satu aspek terkait dengan cara terbaik melindungi anak-anak ini. Banyak dari anak-anak ini yang dibawa ke Suriah dan diindoktrinasi oleh orang tua mereka. Kita memiliki UU Perlindungan Anak di Indonesia,1yang mengharuskan anak berada di bawah pengawasan orang tua mereka. Hal ini dapat menimbulkan tantangan karena hal itu tidak berarti kepentingan terbaik si anak, yang seharusnya hal terpenting.2
Masalah lain yang kami perhatikan adalah bahwa anak-anak yang dibawa ke Suriah dan kembali telah terkena situasi yang membuat mereka mengalami trauma. Ketika mereka tiba di pusat rehabilitasi, kami memeriksa mereka dan menemukan bahwa sebagian besar dari mereka telah menghadapi situasi traumatis, baik selama mereka berada di pusat penahanan atau hanya karena perpisahan dari orang tua mereka, atau situasi lain yang menyebabkan trauma.
Namun tantangan lain yang kami perhatikan dalam tiga tahun terakhir adalah bahwa perlindungan hukum tidak cukup bagi anak-anak yang, tentu saja, adalah korban konflik bersenjata, tetapi yang juga diduga melakukan tindak pidana di bawah sistem hukum domestik. Salah satu kasus yang dapat saya ceritakan adalah terkait dua anak, satu berusia 14 tahun dan yang lainnya berusia 15 atau 16 tahun, yang telah dikirim ke pusat rehabilitasi. Mereka berperilaku baik selama enam bulan mereka di sana, dan berdasarkan hal ini, petugas pusat rehabilitasi menilai dan merekomendasikan mereka siap untuk dikirim pulang. Namun, polisi mengirim mereka ke pengadilan, di mana mereka dijatuhi hukuman masing-masing enam bulan dan sembilan bulan penjara, tanpa mempertimbangkan enam bulan yang telah mereka habiskan di pusat rehabilitasi. Kami sekarang mengadvokasi alternatif langkah-langkah keadilan restoratif untuk anak-anak ini dan orang lain dalam situasi serupa.
Ada juga tantangan begitu anak-anak kembali ke rumah. C-SAVE membantu anak-anak memiliki akses ke sekolah, tetapi sayangnya, masyarakat dan masyarakat sering mendiskriminasi anak-anak ini, mengklaim bahwa sekolah yang menerima anak-anak ini adalah sekolah “teroris”. Jadi, jelas bahwa ada banyak tantangan yang dihadapi anak-anak ini, termasuk masalah hukum, sosial, psikologis dan perlindungan.
Bagaimana dengan anak-anak yang terpisah dari orang tua mereka? Tantangan spesifik apa yang mereka hadapi?
Ada dua skenario utama untuk anak-anak yang kembali yang pernah terpisah dari orangtua mereka. Yang pertama, anak-anak yang masih memiliki orangtua tinggal bersama orangtua mereka. Yang kedua, anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau keluarga. Untuk yang terakhir, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia, pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan anak dan mencari tempat tinggal bagi mereka. Dalam keadaan seperti ini pemerintah sering mengirimkan anak-anak ke pesantren untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan. Pesantren-pesantren ini menerima dan memberi mereka tempat tinggal, pendidikan dan sarana untuk bertahan hidup.
Apa persepsi masyarakat setempat terhadap anak-anak ini setelah mereka kembali ke rumah? Apa yang bisa dilakukan untuk mendorong masyarakat untuk menerima anak-anak ini?
Ketika anak-anak ini berintegrasi kembali ke masyarakat, mereka menghadapi stigma sosial bahwa mereka pernah terkait dengan kelompok teroris. Mereka juga menghadapi diskriminasi di antara anak-anak lain ketika mereka bermain, dan dari orang-orang yang tahu bahwa mereka telah ke Suriah atau Turki dan telah dikaitkan dengan kelompok bersenjata.
Masyarakat sipil dapat memberdayakan anggota masyarakat untuk memastikan bahwa anak-anak ini tidak merasa ditinggalkan atau berbeda dari yang lain. Dengan terasing dan distigmatisasi, hal ini menimbulkan kesempatan bagi anak-anak ini untuk kembali ke jalan yang salah dan masuk kembali ke kelompok teroris yang disebut. Oleh karena itu, sangat penting bahwa masyarakat sipil dan anggota masyarakat bertindak sebagai pelindung garis depan untuk memastikan bahwa anak-anak ini terintegrasi kembali dengan aman ke masyarakat.
Berdasarkan pengalaman, kami sadar bahwa membuat publik tahu tentang siapa dan dari mana anak-anak itu berasal sangat tidak menguntungkan anak karena penyebaran informasi semacam itu bisa menjadi kontraproduktif. Alih-alih membuka peluang bagi mereka untuk memulai lembaran baru hidup mereka, hal itu bisa menimbulkan stigmatisasi lebih lanjut. Jadi ketika C-SAVE bekerja dengan masyarakat, kami memastikan bahwa hanya tokoh penting masyarakat-lah yang mengetahui identitas dan masa lalu anak-anak ini. Kami mempersiapkan mereka untuk menjadi garda depan dengan membuat mereka memahami langkah-langkah deteksi dini kemungkinan rekrutmen ulang oleh kelompok bersenjata serta langkah-langkah pencegahan sehubungan dengan stigmatisasi anak-anak ini. Ini melengkapi mereka dengan alat untuk memahami, toleransi dan empati dengan anak-anak. Kami mendorong masyarakat untuk mempromosikan kegiatan sosial mereka dengan cara yang lebih inklusif sehingga dapat membangun kekompakan sosial, sehingga meningkatkan kapasitas tangguh yang dimiliki masyarakat setempat dalam menghadapi individu yang telah terkena dampak konflik bersenjata. Kami memiliki diskusi komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko ideologi ekstremis kekerasan. Untuk diskusi, kami menggunakan video animasi tentang apa yang dikatakan UU Anti-Terorisme untuk melindungi orang-orang. Kami juga menyiarkan video pendek yang menceritakan kisah kehidupan mantan orang yang dideportasi atau yang kembali. Kami bekerja sama dengan tokoh agama setempat, terutama ulama perempuan, untuk mengadakan diskusi dengan majelis ta’lim tentang bagaimana menerjemahkan ajaran-ajaran agama ke dalam tindakan konkret menerapkan empati, mempromosikan toleransi dan meningkatkan kegiatan sosial demi kebaikan orang lain.
Empati adalah keterampilan inti dalam membangun kapasitas ketahanan masyarakat, dan inilah yang kami coba capai melalui keterlibatan kami dengan masyarakat setempat. Empati harus diwujudkan melalui tindakan. Kami mendorong kelompok masyarakat yang berbeda untuk menghasilkan inisiatif kreatif untuk kegiatan sosial mereka. Misalnya, kelompok keagamaan perempuan di masyarakat setempat menjalankan kegiatan doa dan, setiap hari Jumat, melakukan apa yang mereka sebut “Jumat Bersih” — hari di mana mereka mendorong masyarakat di masyarakat setempat untuk membersihkan rumah, jalan, dan lingkungan mereka. Ini adalah salah satu contoh bagaimana empati dapat diterjemahkan ke dalam kegiatan konkret.
Contoh lainnya adalah kegiatan yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya vaksinasi bagi anak-anak oleh kelompok kesehatan setempat di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk melawan narasi kelompok radikal yang mengklaim bahwa vaksin itu haram. Sebagai komunitas lokal, penyebaran informasi yang salah tersebut merugikan semua orang, terutama bayi dan balita, dan empati pasti berperan dalam melawan narasi-narasi berbahaya ini. Kami mendorong jenis kegiatan ini untuk mempromosikan empati.
Ada narasi di media tentang “ekstremisme kekerasan” dan “radikalisasi” anak-anak, yang kadang-kadang bahkan diberi label “anak-anak teroris”. Apa risiko dari jenis narasi ini?
Ini adalah masalah lain yang dihadapi oleh anak-anak. Cara media membingkai narasi sangat cerdik dan, sayangnya, liputan berita oleh beberapa media tidak mempertimbangkan dampak narasi mereka untuk masa depan anak-anak itu. Kami telah memperhatikan bahwa dampak narasi tidak hanya pada mereka yang kembali dan dideportasi, termasuk anak-anak, tetapi juga masyarakat yang lebih luas. Misalnya, ketika mereka diwawancarai oleh perusahaan TV nasional, tujuan dari program ini adalah untuk mendidik publik tentang pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman mereka yang kembali — bagaimana mereka terjebak dan direkrut. Namun sayangnya, sebagian besar penonton menyalahkan orang-orang yang kembali, dan praduga tentang kesalahan dilemparkan ke mereka dengan memberi sanksi sosial yang berat seperti stigmatisasi dan pengasingan. Memang bukan hal yang mudah untuk mengontrol sudut pandang seluruh basis penonton, tetapi ini adalah tantangan yang harus dipertimbangkan oleh semua media agar memberi dampak negatif yang sekecil mungkin pada orang-orang yang kembali ini. Karena ini adalah liputan media nasional, penyebaran kebencian yang luas terhadap orang-orang yang kembali memiliki implikasi yang parah dan drastis.
Untuk mengatasi hal ini, kami menyelenggarakan pelatihan media dan diskusi dengan media untuk mendorong liputan berita yang empatik, mengingat masa depan anak-anak dan mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat luas, di mana ada risiko bahwa beberapa orang akan memilih anak-anak yang teridentifikasi atau muncul di media, atau menyalahkan mereka. Ketika kita mendidik media, kita pertama kali berdiskusi dengan mereka mengangkat terkait dengan perspektif anak-anak dan perspektif penonton. Ketika media mendekati kita untuk melakukan wawancara tentang orang yang dideportasi atau orang yang kembali — kebanyakan orang dewasa, tapi terkadang juga anak-anak — kami memastikan bahwa wawancara dilakukan hanya secara sukarela. Ketika mereka setuju untuk diwawancarai, makalah formulir persetujuan harus ditandatangani oleh orang yang diwawancarai dan perwakilan media. Formulir ini mencantumkan aturan dan perjanjian seputar apa yang dapat dilaporkan dalam berita berdasarkan wawancara. Ini adalah beberapa langkah yang kami ambil untuk “mendidik” media.
Harapan ke depan, langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk memastikan bahwa anak-anak yang terkena dampak dapat mengatasi stigma, bergabung kembali dengan masyarakat dan menjalani kehidupan normal? Apakah ada “kisah sukses” tertentu yang memberi Anda harapan?
Ke depan, kami akan fokus untuk mengatasi semua tantangan yang telah saya sebutkan sebelumnya: bekerja untuk memperkuat perlindungan hukum anak-anak, termasuk mencari langkah-langkah keadilan alternatif dan bekerja dengan polisi, hakim, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa ada perlindungan hukum yang kuat untuk anak-anak ini. Kedua, kami ingin memastikan bahwa masyarakat adalah ruang yang aman di mana anak-anak dapat diterima dan dapat menjalani kehidupan normal mereka tanpa stigmatisasi. Kami bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, ketahanan dan empati mereka untuk membangun kepercayaan dan kohesi sosial, sehingga ketika para deportasi dan returnees ini direhabilitasi ke dalam masyarakat, tidak ada persepsi negatif terhadap penerimaan mereka. Ketiga, dalam waktu dekat kita ingin fokus pada anak-anak tanpa keluarga atau orang tua. Kita tahu bahwa ada ratusan anak Indonesia di Suriah saat ini, di kamp-kamp pengungsi, yang tidak memiliki orang tua, jadi kita perlu menyiapkan rumah yang ideal bagi anak-anak ini ketika mereka kembali.
Satu contoh cara yang sukses adalah penanganan anak terkait pemboman Surabaya 2018 di Provinsi Jawa Timur. Setelah pengeboman, mereka ditolak oleh komunitas mereka sehingga tidak bisa kembali. Sekarang, mereka tinggal dan belajar dengan anak-anak lokal lainnya di pesantren. Ketika mereka pertama kali datang ke pusat rehabilitasi, mereka dipandang radikal, diindoktrinasi oleh orangtua mereka, dan mereka sendiri sangat trauma. Melalui upaya kami, mereka pulih dari trauma dan siap untuk pulang, tetapi karena masyarakat telah menolaknya, pemerintah perlu mencari tempat lain untuk mereka. Pemerintah mampu mengidentifikasi pesantren yang bersedia menerima mereka, dan sekarang mereka perlahan tapi pasti bergabung dengan masyarakat di sana.
Untuk memahami sudut pandang, dalam konteks budaya Indonesia, pesantren, atau sekolah Islam berasrama, memiliki kontribusi penting dalam pendidikan anak-anak baik dalam hal pendidikan formal maupun informal, termasuk pendidikan agama. Untuk anak yang dideportasi dan dipulangkan, harus ada mekanisme reintegrasi sosial untuk memastikan bahwa ada keluarga yang akan mengurus anak-anak ini, bahwa masyarakat akan menerima kembalinya mereka, dan bahwa ada peluang untuk re-sosialisasi. Dalam kasus anak yatim/piatu, kecuali keluarga besar ada yang merawat mereka, maka lembaga seperti pesantren yang akan menyediakan perawatan dan pendidikan rumahan di luar rumah keluarga. Mereka memberikan perawatan dan pendidikan penuh waktu berdasarkan prinsip-prinsip Islam.
Kami menghadapi beberapa tantangan dalam pekerjaan kami, tetapi kami telah menemukan solusi dan terus berusaha untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak-anak dipertahankan dan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk masa depan.
Apakah ada hal lain yang ingin Anda bagikan dengan pembaca kami?
Untuk menekankan kembali apa yang sudah saya sampaikan, kami memiliki kekhawatiran tentang anak-anak ini diserahkan ke pengadilan. Kami bekerja sama dengan polisi dan jaksa untuk mengembangkan pemahaman bersama dan perlakuan yang lebih baik untuk anak-anak.
Kami juga berencana untuk meninjau kembali kebijakan yang ada terkait perlindungan hukum anak-anak, dan untuk bekerja sama dengan penegakan hukum agar sistem berpihak pada kepentingan terbaik anak-anak. Tantangan saat ini dengan sistem pemasyarakatan adalah bahwa banyak kasus perekrutan anak terjadi di dalam penjara. Kekhawatiran mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang sistem peradilan remaja terkait dengan pendekatan hukuman yang masih dikejar oleh penegakan hukum meskipun penekanan hukum pada keadilan restoratif.
Sistem peradilan remaja Indonesia sudah progresif. Pada 2012, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan undang-undang tentang sistem peradilan remaja yang memprioritaskan pengalihan, meningkatkan usia tanggung jawab pidana dari 8 hingga 12 tahun, dan mendorong penggunaan praktik peradilan restoratif. Undang-undang itu diberlakukan pada 2014. Hukum menyatakan bahwa anak-anak tidak boleh dipenjara, kecuali dalam keadaan luar biasa. Namun, banyak orang Indonesia yang masih belum mengetahui UU itu dan pentingnya memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak, terutama dalam kasus anak-anak yang dipaksa melakukan kejahatan oleh orang lain seperti orang tua mereka atau pengaruh eksternal lainnya. Ini harus dipertimbangkan oleh sistem peradilan remaja, dan kami terus bekerja untuk memastikannya.
Referensi:
2. Penting untuk dicatat bahwa Indonesia adalah salah satu pihak dalam Konvensi Hak Anak, yang menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama berdasarkan Pasal 3. Indonesia juga merupakan pihak dari Protokol Opsional tentang Anak di Indonesia. Konflik Bersenjata, yang memberikan jaminan dan perlindungan lebih lanjut bagi anak-anak korban konflik bersenjata.